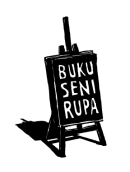Sebuah pemandangan biasa di Surabaya: mobil dan motor salip-menyalip, terbirit-birit seperti dikejar setan. Dering klakson dan umpatan khas Suroboyoan sahut menyahut. Tapi, di gapura perbatasan antara Jl. Plampitan Gang VIII dan Jl. Ahmad Jais, semua itu dipaksa berhenti. Mobil tak mungkin bisa masuk lewat gang yang lebarnya hanya sedepa itu. Sedangkan motor harus dituntun masuk. Bapak-bapak yang sedang duduk di teras Balai RW02 menyapa saya dan mempersilakan masuk, “Mau ke acaranya UNAIR ya? Monggo, monggo, masuk saja lewat gang ini”. Hiruk pikuk kota seketika digantikan dengan suasana gang kampung yang lengang, tawa anak-anak bermain di depan rumah dan kicau burung yang sudah jarang saya dengar. Maka sampailah engkau di Kampung Plampitan.
Kampung ini tampak biasa-biasa saja. Bukan sebuah kampung wisata dengan sudut-sudut instagrammable, signage cantik ataupun mural berwarna-warni. Harta kebanggan di kampung ini hanyalah rumah masa kecil Roeslan Abdulgani. Ia adalah tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah Konferensi Meja Bundar dan Konferensi Asia-Afrika. Selama periode awal Indonesia merdeka ia memegang berbagai macam jabatan publik—mulai dari Menteri Luar Negeri, Menteri Hubungan Rakyat, hingga Menteri Penerangan. Meski, jujur sajalah, seberapa banyak dari kita yang masih mengingatnya?

Lantas, mengapa Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads (AIIOC), memilih Kampung Plampitan sebagai tempat penyelenggaraan proyek seni bertajuk “Ritus Liyan / Mundane Rites”?
Melalui penuturan Anitha Silvia, manajer program dari Ritus Liyan, pertanyaan yang sama rupanya juga dilontarkan oleh warga Kampung Plampitan sendiri. Barangkali justru karena warga luput mengidentifikasi hal-hal yang luar biasa dari kampungnya sendiri, menjadi alasan tepat untuk menyelenggarakan proyek seni yang membicarakan hal-hal keseharian ini.
Jauh-jauh hari, sosiolog Erving Goffman meyakinkan kita bahwa selalu ada yang tersembunyi dalam interaksi keseharian yang barangkali tampak biasa, berulang, dan membosankan. Ia menyebut ini sebagai micrososiologi, bahwa memahami tatanan interaksi keseharian dalam sebuah komunitas adalah kunci untuk memahami bagaimana seseorang mengembangkan identitas individu dan kelompok, bagaimana hubungan dibentuk dan dijalankan, serta juga bagaimana sistem eksklusi dan penindasan terbangun.
Dalam konteks Kampung Plampitan, bagaimana warga hidup berdampingan dengan makam tua Belanda, mengelola sumber air secara kolektif, cangkrukan atau jalur lintasan penjaja sate setiap sore, adalah bentuk-bentuk interaksi keseharian yang tampak banal namun jika ditelaah lebih jauh bisa mengungkap struktur sosial dari kehidupan warga di Kampung Plampitan.

Pameran Ritus Liyan yang berlangsung 24-31 Mei 2024 mengajak seluruh bagian darinya—pengunjung, perupa, panitia penyelenggara, serta warga—untuk membaca keseharian warga Kampung Plampitan sebagai ritus penuh makna dan tanda. Pameran ini dikuratori oleh Bintang Putra dan Aarti Kawlra serta melibatkan sebelas perupa. Tujuh diantaranya adalah peserta lokakarya yang diadakan di bulan Maret: Fildzah Amalia, Gata Mahardika, Kenny Hartanto, Lutfiah Setyo Cahyani, Pingki Ayako, Ryan Herdiansyah, dan Tasyha Febrycha Valentine. Ditambah dengan Cahyo Prayogo dan Redi Murti sebagai perupa undangan, juga Burhan dan Kelompok Batik Peneleh perwakilan dari Kampung Plampitan sendiri.
Menjejalkan Seni dalam Kampung
Ditemani anak-anak kecil yang bermain layangan, saya mengamati poster-poster informasi acara yang disusun seperti menara di tengah lapangan voli. Anak-anak ini seperti tak terganggu dengan adanya dua instalasi menara yang menduduki sebagian ruang bermain mereka. Seperti Pak Mudaih, penjaja sate keliling, tak terganggu dengan pos tempat peristirahatannya yang dipajangi karya-karya drawing Kenny Hartanto. Seperti rombongan pengunjung di teras Pak Burhan yang tak kunjung bubar selepas tengah malam, jelas tak mengganggunya karena terus melarisi pentol dan kopi dagangannya.

Karena membicarakan tentang keseharian warga kampung, sementara sebagian besar para seniman yang terlibat tidak ada yang tinggal di kampung tersebut, pada awalnya saya menduga karya-karya Ritus Liyan sangat rentan untuk mereduksi kompleksitas kehidupan warga, menjadikan mereka objek tontonan dan bukan subjek yang aktif berpartisipasi. Namun dugaan itu meleset. Batas antara warga dan partisipan melebur. Manajer program dan kurator sepertinya memang sudah lama berkutat dengan kampung-kampung di Surabaya. Melalui berbagai percakapan dengan seniman peserta, mereka mengatakan mentor dan kurator kerap menekankan bahwa proyek mereka harus berkolaborasi secara adil dengan warga. Karya-karya yang dibuat berfungsi untuk mengamplifikasi narasi yang muncul dari penduduk Kampung Plampitan.
Dalam perjalanannya sudah pasti tak mudah untuk memenangkan hati para warga. Saya rasa proses para perupa dan panitia tercermin dengan sangat tangible melalui kedekatannya dengan warga. Mulai dari bapak-bapak tongkrongan di Balai RW yang informasinya menggantikan fungsi banner, hingga anak-anak yang begitu mudahnya mengajak pengunjung berkenalan, semua mendukung suasana hangat dan akrab.
Alur pameran dipikirkan dengan cukup baik, diterjemahkan oleh Fanrong Design Studio melalui peta yang tertera pada booklet dan penanda di permukaan paving sepanjang jalan kampung. Gang VIII ke Gang XI ke Gang I Kampung Plampitan menjelma menjadi ruang pamer alternatif yang mengajak pengunjung berjalan kaki menyusuri kampung kota sembari digerogoti panasnya Surabaya. Bukankah berjalan kaki sudah menjadi ritus yang kian asing bagi warga kota?

Pun bila kamu payah dalam membaca tanda jalan dan tersesat, kamu akan bertemu dengan seorang bapak paruh baya yang selalu berkeliling menggunakan sepeda mini velo, membuatnya nampak tidak proporsional. Ia akan membawamu ke jalan yang benar sembari melaporkanmu lewat walkie-talkie yang selalu ia bawa. Ya, nyasar juga merupakan sebuah ritus yang perlu sesekali kamu alami.
Menurut biro arsitektur SB301 yang dipilih menjadi exhibition designer, area pamer ditentukan berdasarkan ruang-ruang negatif atau nirfungsi. Bukan hanya untuk menghindari intervensi terhadap ruang hidup warga, mereka juga berharap, area-area tersebut dapat difungsikan kembali oleh warga bahkan setelah Ritus Liyan berakhir. Salah satu kerja terberat preparator adalah menyulap sebuah bangunan di Gang VIII sebagai ruang pamer utama. Beberapa hari sebelum pembukaan pameran, bangunan ini hanyalah rumah tua yang lama mangkrak, dengan atap yang telah runtuh sebagian, penuh sampah dan akar tanaman. Di bangunan yang telah disulap menjadi “galeri” inilah sebagian karya perupa bernaung.
KRAAK! Saya masuk ke dalam ruang itu dengan merobek sebuah karya instalasi kolase kain perca yang menutupi lubang besar bangunan runtuh ini. Selembar karya milik Lutfia Setyo berjudul “Menumbuh Kasih Selepas Batas” memang dibuat untuk dirobek pengunjung. Ia tertarik dengan praktik border-hacking yang dilakukan warga khususnya pada pagar rumah mereka. Ia melihat, pagar di Kampung Plampitan tidak berfungsi untuk membatasi, melainkan untuk menjadi penghubung. Sepanjang kampung, pengunjung dapat mengamati bagaimana pagar-pagar pendek difungsikan sebagai jemuran, tempat bercocok tanam, juga ruang obrol antarwarga.
Karya Setyo sekaligus menjadi simbol dari fleksibilitas batasan-batasan di Kampung Plampitan, menciptakan dan menghapus batasan semudah merobek instalasi Setyo dan membiarkannya kembali tersingkap. Narasi yang padat ini berhasil disampaikan secara sederhana, spontan, dan partisipatif, melibatkan pengunjung untuk merasakan pengalaman warga, serta memikirkan ulang peran pagar dan batasan. Aduh, uapik!

Pagar juga menjadi checkpoint laju modernisme yang patut dicatat. Diskusi mengenai pagar ini mengingatkanku pada potongan tulisan Ray Bradbury dalam novel dystopia Fahrenheit 451:
My uncle says there used to be front porches. And people sat there sometimes at night, talking when they wanted to talk, rocking, and not talking when they didn’t want to talk. Sometimes they just sat there and thought about things, turned things over. My uncle says the architects got rid of the front porches because they didn’t look well. But my uncle says that was merely rationalizing it; the real reason, hidden underneath, might be they didn’t want people sitting like that, doing nothing, rocking, talking; that was the wrong kind of social life.
Setelah membangun pagar-pagar yang tinggi menjulang, kemudian apa? Modernisme rasanya melaju terlalu cepat, tapi kemana tujuannya? Seperti apakah kehidupan sosial yang sesungguhnya kita harapkan di masa depan?
Perilaku kita mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi perilaku kita. Sejauh mana pagar-pagar yang tinggi di hunian perkotaan menciptakan jarak dan keterasingan? Sementara yang saya alami di kampung, kebersamaan dan keterbukaan dengan mudahnya menjadi ritus keseharian warga. Bergeser dari ruang pamer utama, di antara bangunan-bangunan tua yang dibangun sejak masa kolonial, sampailah saya di Jalan Megawati. Konon, di sinilah tempat Megawati, putri Sukarno, bermain dengan teman-teman masa kecilnya. Di persimpangan jalan itu dibangun sebuah gazebo berkelir merah tempat kami duduk beristirahat melepas lelah.

Kampung Plampitan adalah kampung tua yang telah eksis sejak Kadipaten Surabaya. Saya mendengar cerita dari warga bahwa toponimi Plampitan berasal dari pengrajin tikar lampit yang dulu banyak tinggal di wilayah ini. Seperti kerajinan pada umumnya, lampit dikerjakan secara kolektif oleh orang-orang biasa yang namanya tidak pernah dicatat sejarah.
Tak ada jejak artefak yang tersisa dari pusat kerajinan tikar di kampung ini. Sehingga cukup menarik ketika seniman Cahyo Prayogo meletakkan potongan tikar lampit berbentuk segitiga dalam instalasi seni media bertajuk “Lampitan”. Instalasi ini terdiri dari beberapa speaker yang dirangkai secara kasar pada sebuah tripod. Melalui instalasi suara tersebut pengunjung bisa mendengar suara Pak Prayit, salah satu warga Kampung Plampitan, bercerita tentang pekerjaan masa mudanya sebagai pedagang kaki lima di muka pertokoan Siola puluhan tahun silam. Dipadu dengan alunan tipis lagu Bis Kota oleh Franky & Jane, pengunjung diantar untuk membayangkan aktivitas Pak Prayit menjual kaos bajakan dan CD bootleg “di bawah lorong pertokoan, di Surabaya yang panas” sembari selalu was-was akan penggusuran oleh Satpol PP. Solidaritas antara Pak Prayit dengan mantan PKL lainnya masih erat hingga hari ini, meski ruang temu mereka telah berpindah dari fisik ke Facebook.
Karya Cahyo secara cerdik menjukstaposisi narasi sejarah tokoh dengan narasi Pak Prayit. Menjadi kritik atas arsip negara dan buku sejarah yang nyaris tak pernah mencatat hal-hal sederhana dan kehidupan sehari-hari orang biasa. Bagi saya karya instalasi Yoyo mengisi ruang kosong yang tak diisi media dan sejarawan. Seni rupa menjadi media alternatif yang dapat mengemas narasi-narasi orang biasa ini dengan cara yang menarik bagi publik.

Menandai hal-hal biasa, dalam pameran Ritus Liyan menandai objek keseharian warga seperti sumur, kanopi bersama, pegupon doro, hingga seonggok tangga kayu yang bersandar di dinding pembatas kampung dengan makam tua Peneleh menjadi obyek liyan yang ditandai dengan caption. Usaha ini bisa ditafsirkan sebagai olok-olok sebagaimana dalam galeri seni kontemporer hari ini di mana saklar listrik atau tabung pemadam kebakaran pun ikut dianggap serius oleh pengunjung. Di Ritus Liyan, apapun yang menarik perhatian pengunjung menjadi layak di “seni”-kan. Kepekaan pengunjung menjadi kunci untuk mengalami dan menemukan obyek-obyek liyan ini.
Barangkali salah satu kekuatan perupa dan kurator adalah mengartikulasikan obyek apapun menjadi sebuah karya seni. Menahbiskan hasil karya warga kemudian menjadi cara subversif untuk memperkaya maupun menantang narasi dominan mengenai Kampung Plampitan. Jika sebelumnya Kampung Plampitan hanya dikenal sebagai versi inferior dari Kampung Peneleh di sebelahnya, kini pengunjung diajak mengenal Kampung Plampitan lebih dalam, menyelami kebiasaan warga yang tinggal di dalamnya, kisah-kisah kecil yang mereka miliki.
Narasi kecil dan pinggiran semacam ini menjadi sudut pandang utama dari Ritus Liyan, mengutip tulisan kurator Aarti Kawlra, bahwa tujuan Ritus Liyan adalah menulis ulang kampung melalui proses dialog dengan masyarakat, tempat, objek, dan aktivitasnya; tidak harus menjadi sesuatu yang eksotis atau luar biasa, namun dapat menarik perhatian pada kehidupan sehari-hari dan martabat masyarakat yang tinggal di sana. Di bagian lain tulisannya, Aarti menjelaskan Ritus Liyan sebagai sebuah perayaan ulangalik ketika seniman-interlokutor menjadi warga dan warga menjadi seniman-interlokutor.
Meski demikian, bagi saya kesenjangan antara karya warga dan karya perupa terasa begitu jelas. Para perupa memang berhasil menemukan hal-hal yang mundane, yang keseharian, tapi karya-karya yang dihasilkan secara visual sangatlah spektakuler, begitu jauh dari yang mundane. Karya-karya kontemporer dan konseptual ini kemudian membuat saya berpikir, apakah warga kampung sungguh-sungguh dapat memahami karya-karya kontemporer yang disajikan Ritus Liyan?
Dalam buku The Society of the Spectacles, Debord melontar kritik bagaimana kehidupan modern didominasi oleh gambar dan representasi yang menciptakan jarak antara manusia dengan realitas yang sebenarnya. Spectacle kota, dalam konteks ini, bisa diartikan sebagai citra kehidupan perkotaan yang sarat kepentingan, kecepatan, dan etalase kapitalisme yang menjauhkan orang dari pengalaman nyata dan hubungan sosial yang otentik.
Ritus Liyan berupaya meringkus jarak ini dengan mengajak pengunjung kembali ke lingkungan kampung yang lebih nyata dan berinteraksi langsung dengan elemen-elemen kehidupan sehari-hari warga kampung. Dengan menempatkan seni rupa kontemporer di ruang hidup warga kampung, para perupa mencoba menemukan dan menonjolkan kenyataan di balik spectacle kota. Mereka memanfaatkan objek-objek biasa dan ritus keseharian kampung sebagai medium untuk menunjukkan realitas dan makna yang mungkin terabaikan dalam kehidupan perkotaan yang sibuk.
Sebuah paradoks pada akhirnya tumbuh. Meskipun Ritus Liyan bertujuan untuk mengungkap kenyataan di balik spectacle kota, hasil akhirnya tetap berupa karya seni rupa yang dikemas dan dipresentasikan sebagai sebuah spectacle baru. Seni rupa kontemporer yang dihasilkan dan disuguhkan kepada pengunjung, meskipun berakar pada kenyataan sehari-hari warga kampung, namun tetap menjadi bagian dari representasi sehingga menciptakan jarak baru antara pengunjung dengan realitas yang ingin ditampilkan.
Berlagak Seperti Warga dalam Keseharian Kampung
Sekarang saya akan menjelaskan tentang betapa menariknya sebuah tangga kayu yang menghubungkan Kampung Plampitan menuju makam tua Peneleh. Makam ini menjadi ruang hijau sekaligus spot favorit anak-anak kampung untuk bermain bola maupun bersantai.
Hubungan antara warga dengan makam begitu intim di Kampung Plampitan. Pengunjung dapat menyaksikan beberapa makam keramat tersebar di antara pemukiman warga. Kampung ini juga berdampingan dengan Makam Belanda Peneleh. Tidak ada yang angker dari makam-makam tersebut. Anak-anak bermain bebas di sekitar makam. Sebagian warga juga sering mengunjungi makam untuk mencari ketenangan batin dan berbagi cerita saat tidak ada teman untuk berbicara. Bagi warga Kampung Plampitan, makam adalah bagian dari ritus keseharian mereka.
Seniman performans Ryan Herdiansyah melihat bagaimana warga hidup berdampingan dengan makam tua leluhur. Baginya, warga Kampung Plampitan akrab dengan pembusukan (decay) dan kesementaraan, entah melalui keberadaan makam-makam yang berdampingan dengan ruang hidup warga atau melalui rumah-rumah kosong yang runtuh secara perlahan. Baik makam ataupun rumah-rumah kosong ini dirawat dengan baik oleh warga. Melalui hal-hal material ini, Ryan menemukan nuansa immaterial, perasaan cinta lintas-dunia dan perlindungan dari leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Seperti tertulis dalam deskripsi karyanya, bahwa “ide-ide tentang kesementaraan pun perlahan menubuh dan tercermin dalam laku sehari-hari warga”.
Dalam Ritus Liyan, Ryan menampilkan performance lecture berjudul “Ancestral Playground” yang dimulai dari kisah personal Ryan tentang mencintai sekaligus merelakan yang telah mati. Saat melakukan performans Ryan membagikan tangkai-tangkai bunga mawar kepada penonton, untuk kemudian diambilnya kembali dan kelopak-kelopaknya dimakan habis. Ia kemudian membalut wajah dengan tali, tangkai mawar yang tersisa dan kayu reruntuhan bangunan yang bisa ia temukan. Pada akhir performans ia melakukan kirab mundur sembari menyeret tangga kayu di salah satu kakinya.

Sebelum melakukan performans, sebuah diskusi publik digelar mengenai budaya kematian dan makam-makam di Kampung Plampitan. Diskusi ini mengundang Prof. Dr. Phil. Toetik Koesbardiati, DFM., PA.(k). dari Museum Etnografi & Pusat Kajian Kematian UNAIR. Ia menyatakan bahwa pelbagai mitos yang mengelilingi kematian dan makam membuat kita menginternalisasi ketakutan akan orang mati dan beranggapan bahwa makam bersifat angker. Bukankah mitos-mitos ini yang membuat kedekatan warga dengan makam menjadi mengejutkan bagi para pendatang? Jika kita semua dipengaruhi oleh mitos-mitos seputar makam, mengapa ketakutan-ketakutan ini tidak berlaku pada warga di Kampung Plampitan?
Metode penelitian modern seringkali menganggap remeh pengetahuan lama. Penemuan demi penemuan, mereka selalu mencari sesuatu yang baru. Mitos dianggap tidak sejalan dengan pendekatan ilmiah positifistik berbasis pada data dan eksperimen. Tidak pasti, tidak mutlak, tidak valid! Maka, studi-studi yang menggunakan narasi dan simbol mitologis sebagai basis data jarang sekali kita temukan.
Sementara masyarakat modern melihat mitos sebagai liyan, sebagian warga Kampung Plampitan justru masih mendekap pengetahuan yang terselubung dalam mitos, terutama terkait dengan keberadaan makam-makam di kampung mereka. Misalnya, mitos tentang Kyai Pasopati, Mbah Ayu dan Mbah Panjang, di mana makam-makam mereka dianggap keramat bagi warga Kampung Plampitan dan pengetahuan-pengetahuan ini memperkaya relasi warga dengan lingkungannya.

Selain berbagai diskusi dan pertunjukan, Ritus Liyan juga dilengkapi program-program pendukung lain yang dibuat berdasar kesepakatan dengan warga seperti rujakan, makan penyetan bersama, hingga cangkrukan. Pengunjung seakan diajak untuk masuk dalam keseharian warga Plampitan dan mengalami secara langsung ritus keseharian tersebut.
Sebuah program bertajuk Mblakrak Kali, pengunjung diajak mengikuti keseharian Pak Djoko, seorang warga yang kerap menyisir sungai untuk meramban tumbuhan untuk dijadikan bibit bonsai. Ketika memandu susur sungai Kalimas, Pak Djoko dengan antusias menjelaskan berbagai jenis vegetasi yang hidup di ekosistem bantaran sungai Kalimas—mana yang bisa diolah menjadi obat, mana yang beracun, dan mana yang bisa tumbuh cantik sebagai tanaman hias. Selama perjalanan, Pak Djoko meramban bibit bonsai yang kemudian dibawanya pulang untuk dirawat dengan penuh kesabaran. Barangkali Mblakrak Kali adalah program paling liyan di antara program lain, karena pengunjung dibiarkan pasif termangu dan hanya mendengarkan narasi panduan Pak Djoko.
Program lain bertajuk Open Studio Plang diselenggarakan atas kerjasama antara Om Burhan, warga Kampung Plampitan yang merupakan seniman pembuat plang, dengan Fanrong Design Studio. Melalui program ini tak hanya tersaji diskusi panjang mengenai peran plang dan pendisiplinan warga kampung. Warga dan partisipan lain juga diajak untuk membuat plang mereka sendiri. Kolaborasi antara Om Burhan dan Fanrong Design Studio ini juga memproduksi plang jalan bertuliskan “Jl. Plampitan II” yang entah mengapa luput dari sentuhan Dinas Perhubungan. Di penghujung acara, plang bootleg berwarna hijau dengan teks putih ini dipasang dan diresmikan oleh panitia.
Oh, to be Mundane
Dalam memoar berjudul Masa Kecilku di Surabaya, Roeslan Abdulgani mengakhiri kenangannya atas Kampung Plampitan dengan refleksi berikut:
“Adalah suatu kekeliruan besar menganggap penghidupan dalam kampung sebagai penghidupan yang tingkatnya rendah seperti yang biasa dikemukakan orang-orang Belanda dulu. Atau suatu kehidupan yang tidak mengenal toto kromo sebagaimana dituduhkan kaum priyayi. Sebab, seperti yang telah saya kemukakan secara panjang lebar di atas, kampung saya ternyata merupakan kampung yang penuh dinamika. Sebuah kampung tempat berbagai macam pengaruh berlalu dan bertemu. Suatu masyarakat rakyat yang mengenal toto kromo, mempunyai watak kolektivisme yang demokratis. Sudah barang tentu, ada pula segi positif dan negatifnya. Dan saya yakin, kampung saya di Plampitan Gang IV itu bukanlah suatu pengecualian; melainkan suatu tipe yang di mana-mana memperlihatkan persamaan. Apa yang hidup dan tumbuh di Kampung Plampitan tentu tumbuh dan hidup pula di Kampung Peneleh, Jagalan, Lawang Seketeng, Pandean, Bubutan, Kramat Gantung, Kawatan, Maspati, Tembakbayan, Kranggan, Tembok, Kedung Rukem, Kedung Klinten, Kali Anyar, Kali Asin, dan sebagainya.”
Kampung kota di Surabaya di masa kolonial adalah pemukiman urban bagi para buruh industri. Maka dari itu, letak kampung selalu strategis sekaligus “tersembunyi” di balik areal industri, komersial, dan perkantoran. Setelah kemerdekaan, kampung kota tempat menjadi tempat tinggal paling masuk akal bagi pendatang yang mencari peruntungan di kota besar. Kampung menjadi solusi tepat karena elastisitas, keterjangkauan, dan lokasinya. Hari ini, kampung kota pun tak lepas dari komersialisasi wisata dan eksotisasi, penuh tekanan untuk berubah sesuai dengan tuntutan pariwisata dan tourist gaze. Sehingga hanya tersisa ruang bagi budaya lokal yang tampak atraktif dan kemedol. Sementara ritus keseharian yang dianggap membosankan harus disembunyikan dengan rapi.

Ketika bicara soal gentrifikasi, tak ayal kita selalu berfokus pada kesenjangan fisik. Namun, perubahan budaya di kota besar sesungguhnya juga menciptakan gentrifikasi kultural. Ritus modern perkotaan—bekerja dari jam 9-to-5 di ruang kantor ber-AC, misalnya—dianggap lebih “bernilai” daripada ritus keseharian di kampung. Berjalan kaki dianggap buang-buang waktu, lebih efektif naik ojek online. Jagongan di balai RW dianggap tidak produktif, lebih profesional work from cafe sembari meneguk iced buttercream tiramisu latte seharga empat puluh ribu. Untuk apa curhat dengan makam bila masih ada ChatGPT yang siap merespon 24/7? Sebelum menjajaki pameran, tajuk “Ritus Liyan” sendiri terasa janggal, seolah-olah membedakan, mengesampingkan, merendahkan keseharian warga kampung yang sebenarnya lazim saja bagi mereka. Namun jika berdiri dalam perspektif modern perkotaan, ritus-ritus keseharian warga kampung ini memang secara struktural diasingkan—liyan.
Dengan menempatkan ritus-ritus keseharian kampung sebagai jalur alternatif modernitas, pameran ini memberinya ruang dalam narasi besar modernitas itu sendiri. Seperti plang “motor harap dimatikan” di gapura Kampung Plampitan yang memaksa pengunjungnya untuk berjalan kaki, pameran ini memaksa saya untuk touch some grass. Sungguh, mana mungkin warga kota berinisiatif untuk menunaikan ritus liyan ini? Setelah mengikuti rangkaian ritus kampung ini, saya rasa justru ritus-ritus modern perkotaan yang kemudian terasa begitu liyan. Saya pun berpikir ulang, kenapa saya selalu buru-buru? Kenapa saya tak mengenal tetangga-tetangga saya? Kenapa segala kegiatan yang tak menghasilkan uang membuat saya merasa gelisah dan bersalah? Aneh, liyan!
Menyudahi kunjungan saya di Kampung Plampitan, gulungan ritus modern perkotaan sudah menanti saya. Kampung Plampitan semakin jauh dan kembali menjadi sesuatu yang asing. Salah satu perupa muda yang terlibat dalam pameran berjalan di sebelahku sambil bergumam, “Andai saja aku bisa tinggal di Plampitan..” Andai kita hidup di sisi lain modernitas. Andai kita dapat menjauhi ritus modern perkotaan yang kita hidupi selama ini. Ah, tapi kami berdua tahu, itu hanya akan berhenti dalam impian. Tenggat pekerjaan menanti, Kawan! Makan apa besok kalau hari-hari dihabiskan bermain-main di Kampung Plampitan?
Postscriptum
Ritus Liyan merupakan pra-acara dari The 13th International Convention of Asia Scholars (ICAS 13) yang akan dihelat di beberapa lokasi di Surabaya pada 28 Juli—1 Agustus 2024. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi icas.asia.