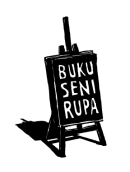Sang Gunung Menyerahkan Jejaknya ke Laut memang judul pameran yang cukup panjang, namun merupakan refleksi terhadap karya-karya yang disuguhkan perempuan perupa Australia-Bali bernama Leyla Stevens. Ini pertama kalinya karya-karya Leyla yang berbasis moving image atau video (baca: gambar bergerak) berdurasi sekitar 9 menit sampai 13 menit dipamerkan di Bali. Karya-karya tersebut berjudul A Line in the Sea (2019) yang dipresentasikan 3 channel melalui 3 televisi yang berderet di salah satu ruang sisi timur galeri; Kidung (2019) yang dipresentasikan 3 channel melalui 3 proyektor dalam ruang besar di tengah galeri; dan Our Sea is Always Hungry (2018) yang dipresentasikan single channel dalam ruang di sisi barat galeri.
Saat berkunjung ke pameran ini, suara-suara video-video sedikit bergema ke sesama. Dalam karya Our Sea is Always Hungry terdapat dua narator, yang pengisi suaranya adalah sastrawan Cok Sawitri dan saya sendiri, kami berbincang serius nan puitis tentang ke-misterius-an cerita-cerita kekerasan 1965-66 di Bali sampai keadaan di Bali saat ini, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Dimulai dari keadaan Gunung Agung yang meletus di tahun 1963 yang sepertinya sering dikaitkan dengan kejadian selanjutnya di tahun 1965, lalu cerita seorang petani dengan kesaksiannya, yang diganggu oleh wong samar (baca: mahluk halus yang merupakan orang tidak kelihatan fisiknya), dan keberadaan pohon serta laut yang menjadi saksi bisu kuburan massal yang terjadi. Visualnya yang kian seperti kolase, membuatmu bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang perlu saya pelajari tentang kejadian ini?

Lalu A Line in the Sea yang merupakan interpretasi ulang tentang keberadaan budaya surfing (baca: papan selancar) yang berkembang di Kuta, Bali, dan didominasi narasi laki-laki dalam film dengan judul “Morning of the Earth” (1972) oleh Alby Falzon. Di sini karya ini kehadiran dua peselancar perempuan Bali yang menunggu ombak dari pantai, mencoba berselancar di titik yang pas, tidak ada percakapan dari mereka, penuh kelembutan lewat musik yang menemani video tersebut. Namun, cerita budaya selancar itu mulainya tidak jauh dari kejadian kekerasan politik yang sebenarnya masih berlangsung di tahun 1971.
Dengan Kidung yang dilantunkan oleh Cok Sawitri di tengah, di antara pijaran pohon-pohon beringin yang menjadi saksi bisu kekerasan politik tahun 1965-66, seakan mempersatukan narasi-narasi yang diceritakan oleh Leyla lewat kedua karya lainnya. Kidung yang dilantunkan Cok Sawitri merupakan “ratapan yang dinyanyikan… dalam hubungannya dengan pohon beringin di lokasi kuburan massal yang tidak diakui dari pembunuhan anti komunis di Bali” (Cush Cush Gallery, 2023).

Posisi karya-karya ini menjadi unik dan membuat kita merefleksikan kembali apa yang ditulis dalam teks kuratorial dari kurator Indonesia berbasis Australia, Bianca Winataputri. Di mana karya-karya yang telah dipamerkan di Australia sebelumnya ini mengkritik bagaimana gunung di Bali sebagai pusat para Dewa-Dewi yang disembahnya dan peradaban kehidupan orang Bali dengan agrarisnya, bergeser karena ekonomi pariwisata massal yang berkembang lebih memilih pesisir sebagai duta paradise (baca: surga). Maka, kekaryaan Leyla tidak lepas dari adanya “kekerasan politik tahun 1965-66, wisata selancar, Garis Wallace, Gunung Agung, dan roh-roh penghuni alam” (Cush Cush Gallery, 2023). Disebutkan juga bahwa,
“Sang gunung menyerahkan jejaknya ke laut merupakan ajakan untuk merefleksikan hubungan kita dengan lingkungan, mulai dari keberadaan hingga tanggung jawab kita di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersama-sama meninjau kembali sejarah dan membangun masa depan kolektif” (CushCush Gallery, 2023).
Dengan itu, Leyla, Bianca, beserta Cush Cush Gallery menyiapkan pameran ini tidak hanya berhenti pada karya-karya yang disuguhkan saja tetapi mengadakan beberapa program publik sebagai bagian dari interaksi bersama masyarakat di Bali. Di antaranya walking tour, diskusi dan lokakarya penulisan. Beberapa diskusi yang dilakukan tersebut menjadi titik-titik temu lautan suara antara audiens dan narasumbernya.

Diskusi yang pertama terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 adalah Artist Talk (baca: bincang seniman) berjudul “Beyond the Frame” bersama Leyla dan kolaboratornya di Bali saat mengerjakan karya-karya yang ada di pameran ini. Selain Leyla, hadir juga Wayan Martino yang berkolaborasi dalam pembuatan ketiga karya sebagai videografer, dan saya sendiri yang berkolaborasi dalam penerjemahan film score Leyla (ia lebih memilih menamakan transkripnya sebagai skor film) serta menjadi salah satu narator di karya Our Sea is Always Hungry.
Dipandu dengan pertanyaan pembuka Bianca, Leyla bercerita secara ringkas kekaryaan yang dipamerkan, bagaimana memang saat itu ia sedang meriset tentang kekerasan politik dan cerita-cerita peristiwa 1965 di Bali. Karya awal videonya adalah Our Sea is Always Hungry. Di dalam video itu, Leyla sempat mengambil sendiri video seorang petani yang naik ke puncak pohon kelapa, lalu berlanjut ke beberapa tempat yang sempat diceritakan keluarganya di sekitar Bali Selatan. Ia lalu berkeliling dengan Wayan Martino mencari tempat-tempat yang bisa dijadikan bagian dari visualisasi karya Leyla, seperti Pantai Masceti, tol Bali Mandara, dan penggambaran wong samar yang diperagakan oleh seniman tari Jacko Wahyu Rizki. Leyla mendapatkan rekomendasi untuk berkolaborasi dengan Martino dan saya dari Founder Ketemu Project, Samantha Tio. Setelah itu, Martino dan saya bergantian berbagi cerita tentang kolaborasi bersama Leyla. Kendala-kendala teknis yang Martino lalui sangat beragam bersama Leyla, keduanya mengawali kariernya sebagai fotografer tetapi malah sama-sama menjadi videografer di sini. Martino merasa bagaimana pengambilan-pengambilan gambar Leyla tidak jauh dari still image dalam fotografi juga.

Sedangkan saya berbagi cerita bagaimana saya nekat menerjemahkan film score Leyla ke bahasa Bali yang tidak saya sepenuhnya kuasai sebagai anak Bali nomaden dan akhirnya dikoreksi langsung oleh Cok Sawitri saat mengisi suara narator (sungguh seharusnya saya minta di-proofread dulu ya sama yang lebih jago basa Bali). Namun di saat yang sama, yang diberikan Leyla bukanlah hal yang mudah diterjemah ke bahasa Indonesia maupun basa Bali juga, karena kata-katanya merupakan kata-kata puitis dalam bahasa Inggris. Lalu, saya pun akhirnya membayangkan beberapa hal yang divisualisasi oleh Leyla itu, karena menerjemahkannya belum tahu apa visualnya. Kemudian saat sempat dikirimkan Leyla hasil akhir daripada karya tersebut, ternyata beberapa imajinasi visualisasinya benar adanya.
Saat diskusi bersama audiens, ada beberapa pertanyaan menarik. Penulis Juli Sastrawan mempertanyakan kenapa di karya Our Sea is Always Hungry ada bagian percakapan kedua narator yang menyatakan seperti, “mari kita berbicara dalam bahasa Bali saja”. Leyla menjawab bagaimana dalam pengalamannya meriset tentang peristiwa yang cukup kelam ini, ada kecenderungan saat berbahasa Bali semua lebih mengalir dan lebih nyaman dibanding harus berbagi dalam bahasa Indonesia. Leyla juga menambahkan bagaimana di negara seperti Australia, tidak semua tahu kalau di Indonesia itu ada berbagai bahasa, menjadi menarik saat di karya itu bisa memberi tahu kalau mereka beralih bahasa – dari bahasa nasional ke bahasa daerah.

Sedangkan Komang Adiartha selaku pemilik Kulidan Space menanyakan tentang kecenderungan karya di dunia tentang Bali maupun yang terjajah yang dulunya sangat penuh pandangan orientalisme dan menjadi sadistik seperti yang ia rasakan lewat karya Leyla. Pertanyaan itu dijawab oleh Leyla, bagaimana ia pun tidak menyadari namun tidak menempatkannya sebagai sadistik. Mungkin memang lebih tentang cerita-cerita yang tidak terlihat sebelumnya, bahwa tidak semua indah-indah saja di Bali. Lalu Bianca meminta saya untuk menanggapinya juga. Saya menambahkan bahwa memang ada kecenderungan dulu hanya dilihat yang indah-indah oleh pihak luar, itu yang ditonjolkan, masih larut terinspirasi dengan Mooi Indie dan tulisan-tulisan tentang Bali yang paradise. Namun, sekarang kita sebagai orang yang dari Bali sendiri memiliki kesempatan yang lebih banyak dan akhirnya bisa mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi secara kritis. Apa saja yang belum diceritakan, contohnya lewat kekaryaan Leyla yang dipamerkan di sini. Dengan itu kita memiliki kesempatan mengeklaim kembali. Kalau dilihat sadistik, mungkin itu jadi salah satu tanggapannya.
Dalam diskusi kedua berjudul “Tri Semaya: past, present, future” pada tanggal 16 Agustus 2023 menghadirkan narasumber periset yang juga dosen I Ngurah Suryawan beserta perupa Made Bayak. Keduanya berkecimpung dalam penulisan dan kekaryaan tentang kekerasan tahun 1965 melalui kolektifnya dulu Klinik Seni Taxu maupun setelahnya. Namun di kesempatan kali ini, mereka juga membahas peristiwa-peristiwa yang dilalui orang-orang Bali di kemudian harinya sampai sekarang. Ditambah, Ngurah yang banyak berkecimpung di Papua beberapa tahun terakhir, juga menyoroti beberapa hal yang serupa tetapi tidak sama yang terjadi di sana.

Yang menarik, di antara diskusi yang cukup interaktif dengan audiens ini, ayah Leyla, Ketut Nugra, hadir di tengah-tengah kita. Ia menyampaikan bagaimana ia sangat penasaran dengan pekerjaan anaknya dan menceritakan sedikit kisah latar belakang keluarganya. Sebenarnya, keluarganya adalah keturunan pandai emas, namun ia tidak meneruskannya karena ketertarikan dengan berkembangnya bisnis surfing (baca: olahraga papan selancar) – yang memperjelas mengapa Leyla mengetahui sekali sejarah peselancar Bali. Saat itu ada beberapa pendatang luar yang mengembangkan surfing di areal Kuta. Ia pun berbagi bagaimana beberapa ide ataupun jargon pariwisata tidak sepenuhnya dibuat oleh orang Bali, seperti Tri Hita Karana (tiga hal keharmonisan) dikreasikan orang Italia. Adapun bandara Ngurah Rai di Tuban, Kuta, awalnya ingin dibuat melayang oleh Presiden Soekarno karena kondisi tanah di area itu, namun pupus idenya saat ia dilengserkan. Maka di saat pariwisata dikembangkan pada tahun 1960-80 itu, ada beberapa ide yang lebih ramah terhadap Bali malah tidak tercapai. Ini seperti halnya bagaimana pariwisata di Bali yang hari ini juga (masih) carut marut.
Ada pun pernyataan penting yang datang dari para narasumber. Pertama, Ngurah Suryawan menyampaikan bagaimana ada dua pengaruh power (baca: kekuasaan) terhadap imajinasi yang dimiliki oleh generasi muda Bali, yakni: pelestari budaya & menjadi tenaga kerja pariwisata. Sedangkan yang memiliki imajinasi alternatif dari kedua ini dan cenderung critical thinking (baca: pemikiran kritis) seakan tidak ada ruangnya. Maka, akan perlu lagi banyak ruang untuk itu, seperti diskusi yang terjadi di CushCush Gallery saat itu. Kedua, Made Bayak melengkapi bagaimana misalnya Tri Hita Karana menjadi slogan dan upacara-upacara atau pengajaran tattwa-upacara agama Hindu Bali yang dilaksanakan mulai menjadi bagian dari slogan juga. Padahal teologi yang ada di dalam agama Hindu Bali sangatlah critical thinking, sayangnya sangat jarang diajarkan secara runut. Maka, jika dibedah kembali, generasi muda Bali bisa saja kritis pada daerahnya dan tidak turut mengikuti imajinasi-imajinasi besar tersebut. Dengan itu memerlukan beberapa, yang dikatakan Ngurah, “oase atau ruang-ruang refleksi”, dimana merefleksikan kembali positioning (baca: posisi) seorang anak muda Bali itu di mana untuk daerahnya ke depannya.

Dalam diskusi ketiga “Collective Memory: Mapping History and Uncovering Untold Stories of Bali” pada tanggal 19 Agustus 2023, menghadirkan narasumber penulis Juli Sastrawan dan kurator Sidhi Vhisatya. Saat ini Juli mendalami isu kekerasan tahun 1965 karena sedang proses menulis buku berdasarkan cerita-cerita yang ia dapatkan di Bali. Di saat yang sama, cerita-cerita tersebut dipetakan secara digital bernama “Situs Ingatan”. Pemantik Juli tertarik dengan isu yang sebenarnya berjarak dengannya dikarenakan ada salah satu kakeknya yang terdiam melamun saat peristiwa meletusnya Gunung Agung tahun 2017, dimana dua tahun lagi di tahun 2019 akan ada pemilu. Peristiwa ini mengingatkan kakeknya pada meletusnya Gunung Agung 1963, selang dua tahun pemilu 1965 juga namun ternyata kekerasan massal pun terjadi. Ia lalu teringat traumanya, saudaranya hilang, dan peristiwa tidak mengenakkan di sekitar rumahnya. Dengan itu, ia mengumpulkan beberapa memori kolektif tentang masa-masa itu dan dampaknya sampai masa kini.
Sedangkan Sidhi yang sejak tahun 2019 ikut membangun Queer Indonesia Archive (QIA) bersama komunitasnya meneliti dan mengarsipkan kembali cerita-cerita kaum queer di Indonesia termasuk di Bali. Mengetahui perbincangan tentang kaum queer di Indonesia sangatlah tidak mudah, maka QIA pun beradaptasi dan bekerja secara fleksibel, bahkan eksperimental. Di diskusi ini ia menghadirkan beberapa cerita yang ia dapatkan terjadi di Bali sendiri. Salah satu koleksi pertama yang didapatkan di Bali adalah foto-foto drag queen dari Komunitas Gaya Dewata/Yayasan Gaya Dewata, sebuah komunitas yang mewadahi dan mengadvokasi LGBTQ di Bali. Sidhi juga membagikan ada penemuan pembentukan larangan terhadap keberadaan queer terjadi di saat-saat penjajahan masih terjadi melalui KUHP, yang menyebabkan perupa luar seperti Walter Spies sempat terjerat undang-undang tersebut. Padahal beberapa suku di Indonesia mengenal keberadaan berbagai gender selain laki-laki dan perempuan.

Hal-hal yang diangkat oleh Juli dan Sidhi mungkin dianggap tabu bagi beberapa bagian masyarakat namun di sini menjadi hal yang penting untuk dibicarakan. Menariknya lagi, diskusi ini yang paling ramai didatangi dan banyak audiens yang berbagi kisah juga. Mau bagaimana pun, cerita-cerita yang untold (baca: tidak terucap) ini perlu diperhitungkan jika kita adalah seorang manusia yang mengapresiasi keberadaan manusia lain di sehari-harinya. Memori-memori kolektif ini sudah seharusnya tidak tertindas dari kehidupan kita. Salah satu audiens yang datang, Agung Alit, pendiri Taman 65 yang menjadi wadah untuk para penyintas maupun yang mencari cerita-cerita tahun 1965, menyatakan: mass massacre, mass grave, mass tourism, mass problem. Tidak bisa dipungkiri kalau inilah salah satu rentetan terjadi di Bali yang dampaknya sampai hari ini–adanya kekerasan massal dan kuburan massal, ditutupi dengan narasi turisme massal dan menjadi permasalahan eksploitasi yang semakin besar.
Sekilas lautan suara yang bertemu di CushCush Gallery ini, sangatlah beragam, menjadi cerita-cerita yang saling melengkapi pameran Leyla Stevens Sang Gunung Menyerahkan Jejaknya ke Laut. Seperti kepercayaan Hindu Bali yang melihat prosesi penyucian terakhir pada Nyegara Gunung di Pura yang berada di gunung dan laut, menjadi proses terakhir dalam upacara kematian sebelum distanakan di tempat ibadah keluarga sebagai leluhur. Apakah jejak-jejak kita sebagai manusia secara kolektif menjadi kisah-kisah yang bisa dinetralisir nantinya di antara gunung dan laut?
***