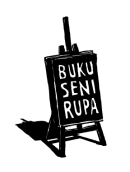Angin bergerak secara perlahan tapi pasti. Langit sore berangsur oranye, nampak cerah dengan awan terserak di sana-sini. Tiba-tiba, dari sebelah arah kanan saya datang tiga perempuan muda yang masih mengenakan seragam sekolah. Dua orang nampak sedang merekam satu orang lainnya yang berkata ke arah kamera: “Halo gaes, sekarang kita ada di Gelaran Olah Rupa!”. Kedua telunjuknya digerakkan ke arah papan yang terpasang di belakangnya. Benar saja, tertuliskan Gelaran Olah Rupa di bagian tengah dari konstruksi yang berbentuk semacam gapura itu.
Diselenggarakan sebagai bagian dari Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) 2025 dan dikurasi oleh Karen Hardini & Tomi Firdaus serta ko-kurator Ghofur S., Gelaran Olah Rupa mengolah gagasan bertamu/perjumpaan. Proses bertamu sebagai praktik sosial diejawantahkan ke dalam proses Residensi Pekan Sowan, di mana seniman dari luar Gunungkidul diundang untuk bermukim dengan warga di pelbagai wilayah Gunungkidul selama satu minggu.
Jika berekspektasi untuk melihat sebuah pameran seni rupa, barangkali Gelaran Olah Rupa tidak akan sepenuhnya memenuhi imaji tersebut. Kita akan menemui serangkaian instalasi seni, betul, akan tetapi lebih dari itu: kita juga mempertanyakan, merekonstruksi, dan mendebatkan bahkan mungkin menolak tatapan, cerapan, dan pengalaman para seniman tentang Gunungkidul. Berangkat dari proses residensi yang relatif singkat, karya seniman partisipan yang dibawa ke dalam ruang pamer diposisikan sebagai ruang kerja yang hidup. Melalui kerangka perjumpaan dan proses bertamu, banyak karya yang kemudian menginkorporasikan interaktivitas dan partisipasi audiens.
Memasuki Wahana Rupa
Penyajian Gelaran Olah Rupa punya tawaran yang khas: strukturnya terbuka tapi tertutup. Lokasi pameran dibentuk lewat sekian scaffolding yang disusun melingkar, sekilas mengingatkan kita akan bentuk wahana tong setan yang akrab dijumpai di pasar malam. Bagian atasnya samar-samar tertutup banyak kain putih berbentuk triangular yang saling bertumpuk dan beririsan. Turut ditautkan kain-kain tipis berwarna putih, kuning, dan merah di bagian luarnya sehingga pengunjung bisa samar-samar mengintip apa yang tertata dan dipresentasikan di dalam “wahana”.

Meski demikian, pemandangan yang bisa dilihat dari luar tetap terbatas dan cukup tertutup. Audiens perlu betul-betul masuk ke dalam untuk dapat mengalami karya-karya secara penuh. Kontradiksi demikian saya pikir efektif untuk mengundang dan menarik orang-orang untuk masuk dan bisa mengapresiasi karya. Ibarat istilah: tak ada white cube*, scaffolding pun jadi.
Keterbukaan venue pameran lantas menjadi tawaran bagaimana seni (di tengah) masyarakat tempatan dipresentasikan. Untuk sekarang, barangkali presentasi di area terbuka dengan fasad luar yang berwarna dan dimensi ruang yang luwes menjadi rancangan program yang berdaya guna untuk masyarakat umum. Pameran tak hanya menjadi objek statis yang membuat orang sungkan untuk masuk dan menyelaminya. Pameran juga bukan hanya jadi momen untuk menyahihkan mana karya yang “layak” untuk dipamerkan dan diperiksa publik. Ia eksis dan mengundang. Ia tidak membuat audiensnya merasa kecil dan sungkan karena berpikiran tak cukup intelek untuk memahami karya seni.
Mengitari Ragam Wajah Gunungkidul
Ketika pertama kali masuk ke dalam ruang pamer Gelaran Olah Rupa, saya langsung mendapati semacam balok monolit di tengah-tengah. Penel putih bersisi delapan tadi berisikan informasi setiap kapanewon atau desa yang dipilih sebagai lokasi Pekan Sowan bagi setiap seniman. Digenapi dengan visualisasi wilayah tempatan, turut dijelaskan secara singkat fenomena yang terjadi di setiap lokasi dan kolaborasi yang kemudian lahir dari perjumpaan seniman tamu dengan seniman, kolektif, atau tokoh serta warga setempat. Di salah satu sisinya juga dilekatkan sebuah televisi yang menayangkan dokumentasi para seniman menjalani residensi singkat tempo hari.
Karena ruang pamer dibentuk melingkar, saya pun perlahan mengitari satu karya ke karya lain. Jika memilih untuk memulai perjalanan searah jarum jam, karya pertama yang akan ditemui adalah karya milik Titik Kumpul Forum dan Raden Kukuh Hermadi. Mengangkat isu mobilisasi lajon atau bepergian bolak-balik, gerak melaju lantas mereka bubuhkan dalam “Catatan 60 km perjam” dengan menggabungkan kegiatan mencukil sebagai bagian dari karya. Di atas sebuah meja, secara partisipatif orang-orang diajak untuk mencukil peta DIY di atas karet linoleum berwarna coklat. Proses mencukil berlangsung secara repetitif, sejalan mengikuti alur. Ia memerlukan ketelatenan dan kefokusan; selayaknya gerak lajon. Di belakang meja, terpasang jahitan karung yang disematkan visualisasi hal yang akan ditemui selagi melakukan mobilisasi. Dari sekumpulan pengendara motor yang menyusuri turunan tajam, kutipan jenaka di ‘bokong’ truk, dan tak lupa petani yang mengangkut setumpuk pakan ternak.
Selanjutnya bisa ditemui instalasi garapan kolaborasi Ikatan Perupa Gunungkidul dengan Nabila Rahma dan Tiang Senja. Karyanya giat – kita bisa melihat daur hidup sesuai tembang macapat dalam visualisasi wayang, mendengar dan membunyikan gerabah yang tergantung dalam susunan kayu, mencecap aroma tanah dalam gundukan gelu, juga meraba buku catatan dokumentasi seniman selama sepekan. “Gelu”, yakni gumpalan tanah berbentuk bulat yang digunakan sebagai pengganjal jenazah saat pemakaman, dipilih sebagai tajuk dari karya ini. Persilangan antara daur hidup, gelu, dan medium tanah menjadi satu tarikan nafas yang seolah mewujudkan entitas baru. Ia membicarakan tanah sebagai salah satu aspek yang lekat dengan Gunungkidul, namun ia juga mengetengahkan narasi yang universal.

Tanah juga menjadi salah satu pintu masuk yang menjembatani karya Sibagz dan Vendy Methodos dengan realitas sosial warga Gunungkidul. Berbicara mengenai ancaman pembangunan dan industrialisasi kawasan karst, saya seketika berteleportasi di tengah pilar-pilar beton yang kelak di atasnya akan dibangun peternakan ayam. Secara jenaka Vendy dan Sibagz bermain dengan tema FKY 2025, menggubahnya secara kontekstual, dan menuliskannya sebagai latar belakang sekaligus judul: “Adoh Ratu, Jogo Watu” (jauh dari raja/pemimpin, menjaga batu). Ketika membahas ihwal pembangunan, wajar saja kita secara gamblang menolak – banyak sekali catatan sejarah dan ragam artefak yang berkata jika pembangunan kelak hanyalah mewujud menjadi tubuh luka bumi. Kehadiran struktur beton dan menyandingkannya dengan biodiversitas asli Gunungkidul secara lebih lanjut mengajak kita sejenak untuk bertanya: Apakah ada yang diuntungkan dari pembangunan ini? Dan siapa yang diuntungkan, begitupun dirugikan dari kesemua proses ini?
“Truh” (air hujan) karya Lambung Kawruh dan AODH mengalirkan pengalaman dan pengetahuan yang menubuh dari masyarakat Petir. Sukarnya mempertahankan air dalam lanskap alam yang didominasi perbukitan karst menuntun warga setempat untuk beradaptasi dengan keadaan. Taktis, air hujan menjadi salah satu cara warga untuk menjadi resilien. Karya mewujud dalam dua bagian. Di bagian belakang, replika inisiasi warga untuk memanfaatkan segala pengetahuannya untuk menjaga setiap butiran air yang jatuh dibentuk. Sekilas jejaringnya mungkin tak beraturan, namun ia fungsional. Atap genteng, ember, kuali, pipa paralon yang semruwet, membentuk ansambel dengan bebunyian yang beragam. Di bagian depan, sebuah pohon dan segunduk bebatuan tumbuh. Keduanya menjelma dua entitas yang saling hidup beriringan dan saling menghidupi satu sama lain.
Kontestasi wajah Gunungkidul semakin didiskusikan dalam “HANDAYANI”, karya milik Endry Pragusta dan Arief Mujahidin. Mengerucutkan identitas satu daerah yang isinya majemuk ke dalam satu hal (atau dalam konteks pameran menjadi satu karya) agaknya mirip tugas sisifus mendorong batu. Berangkat dari narasi keberagaman, karya ini kemudian membuka ruang interaksi dengan audiens lewat menggambarkan makna handayani ke papan tulis menggunakan kapur berwarna-warni. Semboyan “Gunungkidul Handayani” lantas menjadi pemantik percakapan dan bukan perkara jargon saja. Bagaimana masyarakat memaknai handayani, lebih-lebih apakah handayani menjadi representasi yang tepat dirasakan oleh warga? Pembingkaian pameran sebagai laboratorium hidup turut diperpanjang karya ini dan saya pikir amatlah mungkin untuk terus memperbincangkan gagasannya, bahkan selepas pameran berakhir.
Gagasan dan praktik penelusuran dilanjutkan oleh Trah Sekar Jagad dan Reza Kutjh melalui “Sepenggal Cerita Tentang Wahyu Gagak Emprit”. Apabila karya sebelumnya menelisik pemaknaan kontemporer, sebaliknya, karya ini berupaya memahami sejarah narasi tempatan yang acap kali tertimbun. Alih media foto arsip dan pembayangan kembali citra masa lampau menjadi salah satu cara untuk mereka ulang narasi yang tidak turut mengalir dalam arus utama. Potongan, pecahan, dan visualisasi sejarah yang disusun dalam bentuk kolase membuat saya sedikit mengimajinasikan sebuah narasi lepas yang non-linear. Dalam presentasi yang demikian, saya semacam ditantang untuk menanggalkan pengetahuan dan pola pikir yang sudah tertanam dan merekonstruksi ulang resepsi yang saya terima, meski hanya sepenggal.
Pelawatan saya yang relatif lambat dari satu karya ke karya lain pada akhirnya terdisrupsi juga. “Babad Sigare Bukit” kolaborasi Mbah Bambang & Mbah Saido (tokoh adat di Tepus Gunungkidul) dengan Survive! Garage memproblematisasikan akselerasi pembangunan yang merusak ritme makhluk hidup setempat. Tak hanya manusia, namun juga hewan dan tumbuhan pun tak lepas dari efek samping pembangunan yang tak terbendung. Percakapan multispesies kemudian diinisiasi dan dimunculkan melalui beragam bentuk: dalam tulisan, lukisan, video, dan pengunjung pun diajak untuk menyambungnya dengan menuliskan apapun dalam meja papan putih.

Masih dalam kerangka interaksi multispesies, Resan Gunungkidul dan M. Shodik dalam “Mambu Ampo, Gégér Labuh, dan Genduren” memanifestasikan ruang hidup dalam tataran ekologis yang lebih sempit dan bisa kita kelilingi. Dengan pohon resan duduk di sentral karya, elemen lain seperti tanah, janur, dan perkakas pertanian diposisikan selayaknya penyejajaran atas semesta besar dan semesta kecil. Beberapa panel surya berbahan tanah juga tertata di bagian depan. Mencatut salah satu panel, “Jauh sebelum adanya bahasa manusia, IRAMA TANAH telah menjadi bahasa TERTUA…”. Dalam nukilan karya demikian, kritik atas pergeseran paradigma yang tidak mengetengahkan pengelolaan ekologi yang berkelanjutan secara subtil dibumikan.
Karya terakhir yakni “Gugur Gunung: Pangan lan Rasa” kolaborasi antara Ibu-ibu KWT Ngalang dan Kolektif Matrahita membawa saya kembali ke ruang domestik setelah menjumpai Gunungkidul dalam ragam wajah dan lokasi. Karya yang mengusung gagasan kerja perawatan ini terasa melebur. Bagi ibu-ibu di Ngalang, kerja perawatan bukanlah konsep melainkan laku keseharian yang hadir di setiap lini kehidupan. Matrahita menyambungkan gotong-royong yang dijalankan ibu-ibu KWT dengan praktik pemanfaatan limbah tekstil. Kain yang melintang dan simbolisasi pernak-pernik kehidupan lantas tidak hanya menjadi wahana alih bentuk, melainkan cara mencatat yang terasa dekat.
Merefleksikan Pengalaman Pasca Gelaran
Adoh Ratu, Cedhak Watu. Makna literalnya ialah jauh dari raja/pemimpin, dekat dengan batu. Tema FKY 2025 ini pun bisa dirasakan ketika melihat karya-karya dalam Gelaran Olah Rupa. Beberapa karya menampilkan dan memperbincangkan isu-isu lingkungan secara eksplisit dan secara materiil, sebagian yang lain mengajak pengunjung untuk merefleksikan kehidupan sehari-hari lewat pendekatan yang lebih subtil.
Saya pikir sah-sah saja bagi suatu pameran untuk menjadi akrobat estetika bagi senimannya. Justru karena menjadi sosok pameris, ia berhak untuk bisa melakukan geliat-geliat sesuai dorongan artistik yang ada dalam dirinya. Akan tetapi, apa yang menjadi resepsi saya selama mengalami pameran Gelaran Olah Rupa tidaklah demikian. Saya merasakan para seniman partisipan, terkhusus yang berasal dari luar Gunungkidul benar-benar datang, bertamu, dan kemudian meramu apa yang mereka alami menjadi karya dengan hati-hati dan kepekaan. Karya yang dipertemukan dengan audiens tidak hanya dihadirkan secara satu arah, melainkan berada dalam ruang dialogis dan tidak mendikte. Alih-alih, warga Gunungkidul juga audiens lain membentuk dan memiliki andil dalam proses kekaryaan.

Ketika direfleksikan kembali, bentuk ruang yang melingkar ibarat sejalan dengan siklus hidup dan ritus masyarakat Jawa yang berulang. Menapaki pameran secara siklikal juga kemudian membuat saya secara lambat namun pasti mengkontemplasikan setiap fase dan perspektif – tidak secara tunggal melalui rasionalitas, melainkan juga melibatkan empati dan daya rasa. “Bagasi pengetahuan” saya yang telanjur dijejali ragam paradigma dan pengetahuan yang tumbuh-berkembang di kawasan urban sejenak tak saya buka. Mengalami gelaran ini membawa saya untuk sejenak memposisikan diri sebagai tamu, sebagai seseorang yang disajikan dengan pelbagai jamuan pengetahuan lokal.
*) Mengacu pada estetika tata ruang pamer maupun galeri mapan yang ditandai dengan bentuk persegi atau persegi panjang, dinding putih, dan sumber cahaya yang biasanya berasal dari langit-langit.